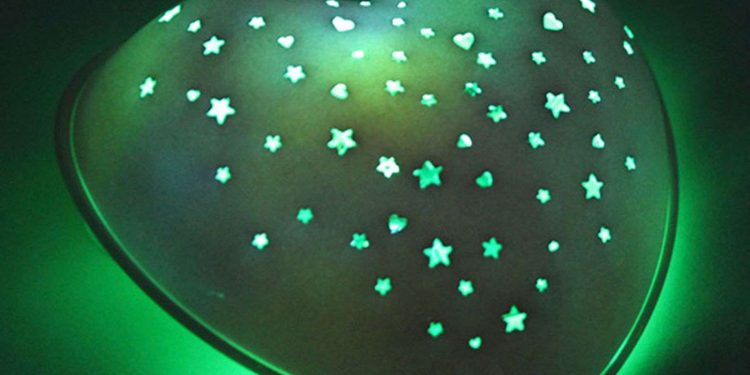ADIL tidak selalu sama rata. Adil tegak secara proporsional. Termasuk terhadap rasa.
Adil terhadap sesuatu yang bisa diukur mungkin mudah. Misalnya, punya anak tiga, maka jatah hak masing-masingnya sekitar sepertiga.
Begitu pun jika punya lima pegawai dengan tanggung jawab yang sama. Maka hak masing-masingnya sebesar seperlima dari jatah anggaran untuk pegawai.
Atau untuk para suami yang beristri lebih dari satu. Maka jatah harinya bisa disamakan satu sama lain. Tidak boleh ada yang kurang atau lebih.
Namun jika soal rasa, mengukurnya hampir tidak mungkin. Selalu saja ada subjektivitas diri yang sulit untuk ditegakkan secara proporsional.
Contoh, punya anak tiga, ada yang nakal dan ada yang baik. Yang nakal tentu kita tidak suka. Dan yang baik, tentu sangat kita suka. Suka dan tidak suka inilah yang akhirnya mempengaruhi takaran keadilan kita untuk mereka.
Pertanyaannya, bisakah kita memberikan perhatian yang sama terhadap semuanya. Baik terhadap yang nakal maupun yang baik. Di sinilah kerumitan tentang adil mulai terasa.
Begitu pun tentang suami yang istrinya lebih dari satu tadi. Untuk jatah hari, mungkin bisa diatur secara adil. Tapi tentang yang disukai dan yang kurang disukai, ukurannya menjadi sangat subjektif.
Masih soal rasa, kadang kita terjebak pada akumulasi suka atau tidak suka yang sulit dilupakan. Misalnya, terhadap anak yang nakal dan baik tadi. Karena yang nakal terakumulasi lama dalam rasa kita, maka stigma buruk terhadapnya seperti tak bisa dilepaskan.
Sementara, sikap nakal atau baik itu tidak permanen. Kalau ada cahaya hidayah mempengaruhi hati seseorang, meskipun sebelumnya ia nakal, maka boleh jadi ia akan menjadi baik. Walaupun baiknya belum stabil.
Nah, di sinilah susahnya. Kita menjadi tidak adil menilai yang tiba-tiba berubah baik itu karena terjebak dalam endapan stigma buruk kepadanya.
Begitu pun dalam cakupan ruang sosial yang lebih luas. Ada saja kelompok-kelompok tertentu yang selalu berbuat buruk. Maka kita pun menstigmanya sebagai kelompok buruk.
Tapi suatu kali, kelompok ini tiba-tiba berbuat baik. Benar-benar baik secara tulus, bukan karena pencitraan atau dibuat-buat.
Pertanyaannya, bisakah kita langsung memberikan apresiasi baik terhadap mereka. Atau, jangan-jangan kita tidak percaya: “Alah paling-paling karena mau pemilu aja!”
Belajar adil memang bukan hanya otoritas para penegak hukum seperti hakim. Kita secara individu pun harus belajar tentang keadilan.
Dan ketika ada kebaikan di pihak yang tidak kita suka, maka kita harus mengapresiasi bahwa mereka sedang baik. Sebaliknya, ketika ada keburukan di pihak yang kita suka, maka harus diakui bahwa itu memang keburukan.
Dalam Al-Qur’an, Allah subhanahu wata’ala mengajarkan kita, “…dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa…” (QS. Al-Maidah: 8)
Yuk, belajar adil dalam dunia rasa kita. Baik buruk itu bukan karena yang kita suka dan benci. Tapi karena memang Allah mengajarkan kita untuk bersikap adil, meskipun kita berat hati mengakuinya. [Mh]